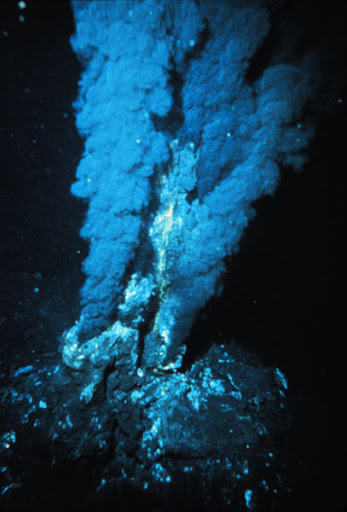Salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang paling terkenal tentang rukun
Islam adalah yang berbunyi : Islam didirikan atas 5 [perkara], [1]
Bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah SWT dan bahwasanya
Muhammad adalah utusan-Nya, [2] Mendirikan shalat, [3] Menunaikan zakat,
[4] Berpuasa di bulan Ramadlân, dan [5] Melaksanakan haji bagi yang
mampu. Hadits tersebut sangat populer di kalangan muslim karena menjadi
tiang atau dasar bagi sendi-sendi syariat Islam. Selain karena menjadi
tiang, alasan kepopuleran lainnya adalah karena Nabi Muhammad SAW
menjelaskan rukun-rukun itu ketika malaikat Jibrîl yang menjelma menjadi
seorang pemuda menanyakannya.
Kata Ramadlân berasal dari akar kata dasar r-m-dl, atau ra-mi-dla yang
berarti “panas” atau “panas yang menyengat”. Kata itu berkembang
–sebagaimana biasa terjadi dalam struktur bahasa Arab– dan bisa
diartikan “menjadi panas, atau sangat panas”, atau dimaknai “hampir
membakar”. Jika orang Arab mengatakan Qad Ramidla Yaumunâ, maka itu
berarti “hari telah menjadi sangat panas”. Ar-Ramadlu juga bisa
diartikan “panas yang diakibatkan sinar matahari”. Ada pendapat yang
menyatakan bahwa Ramadlân adalah salah satu nama Allah SWT. Tetapi,
penulis merasa pendapat ini lemah karena tidak memiliki argumentasi
literal.
Demikianlah istilah bulan Ramadlân diambil dari kalimat
ramidla-yarmadlu, yang berarti “panas atau keringnya mulut dikarenakan
rasa haus”. Keterangan-keterangan tentang lafadz Ramadlân ini
disampaikan oleh Muhammad bin Abû Bakar bin Abdul Qâdir Al-Râzî [w. 721
H.] dalam kamus Mukhtâru-sh-Shihhâh dan Muhammad bin Mukarram bin
Mandzûr Al-Mashrî [630-711 H.], yang terkenal dengan sebutan Ibnu
Mandzûr, dalam karya monumentalnya, Lisânu-l-‘Arab.
Sedangkan puasa dalam bahasa Arab disebut Shiyâm atau Shaûm –keduanya
sama-sama kata dasar dari kata kerja Shaa-ma–, yang secara etimologis
berarti menahan dan tidak bepergian dari satu tempat ke tempat lain
[Al-Syaukânî, 1173-1255 H., Fathu-l-Qadîr]. Shiyâm atau Shaûm merupakan
qiyâm bilâ ‘amal, yang berarti ‘beribadah tanpa bekerja’. Dikatakan
‘tanpa bekerja’ karena puasa itu sendiri bebas dari gerakan-gerakan
[harakât], baik gerakan itu berupa: berdiri, berjalan, makan, minum dan
sebagainya. Sehingga, Ibnu Durayd –sebagaimana dinukil dalam Al-Âlûsî–
mengatakan bahwa segala sesuatu yang diam dan tidak bergerak, berarti
sesuatu itu Shiyâm, sedang ber-puasa. Selain itu, puasa, sebagaimana
penulis sebutkan di atas, berarti ‘menahan’ dari sesuatu pekerjaan. Dan
‘sesuatu’ itu telah ditentukan oleh syariat. Dengan begitu, dalam
syariat, puasa memiliki pengertian tersendiri.
Makna puasa yang “menahan” ini juga terlihat jelas tatkala kita menelusuri sejarah bahasa shiyâm atau Shaûm.
Ibnu Mandzûr, pakar sejarah bahasa Arab yang hampir tiada duanya, dalam
hasil pelacakannya atas asal-muasal kata, mendefinisikan Shaûm sebagai
“hal meninggalkan makan, minum, menikah dan berbicara”. Definisi ini
adalah definisi paling asli dan sahih dalam sejarah bahasa Arab. Ini
cocok dengan keterangan Al-Qur’an, misalnya, pada kisah Sayyidah Maryam
saat menjawab cemoohan-cemoohan orang-orang kepadanya, "Sesungguhnya
aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku
tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini" [QS.
19:26]. ‘Puasa’ yang dimaksud Sayyidah Maryam di situ adalah “menahan
untuk tidak bicara”.
Di sini, sifat ‘menahan’ menjadi titik atau letak perbedaan antara
puasa dengan amal ibadah yang lainnya. Apapun amal ibadah seseorang,
pasti akan dapat diketahui dari sisi dhâhir atau luarnya, seperti
shalat, haji dan sebagainya. Tetapi, untuk puasa tidak bisa diketahui
dan tidak bisa diperlihatkan dengan gerakan-gerakan dzahîr atau fisik.
Pantaslah jika Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa satu-satunya ibadah
yang tidak bisa dicampuri riya’ --memperlihatkan kebaikan tertentu--
adalah puasa.
Melihat keterangan-keterangan Ibnu Mandzûr dan Al-Râzî tersebut di
atas, baik tentang makna Ramadlân maupun puasa, ada indikasi bahwa
seolah-olah turunnya syariat puasa, setidaknya, bersamaan waktunya
dengan kelahiran bulan Ramadlân. Hal tersebut bisa dibenarkan,
tentunya, dikarenakan kedua kata itu memiliki relasi makna yang dekat
dan saling bersentuhan, yaitu sama-sama ‘panas’ atau ‘kering’ yang
disebabkan ‘berpuasa’.
Muncul pertanyaan, sejak kapan pastinya bulan Ramadlân itu ada dan
sejak kapan pastinya puasa Ramadlân disyariatkan, sehingga beliau
berdua mengaitkan syariat ini dengan maknanya sebagai “panas, kering
atau haus”? Dan sejak kapan puasa diberlakukan kepada umat manusia?
Bagaimana dengan puasa-puasa terdahulu yang dilakukan tidak di bulan
Ramadlân? Pertanyaan-pertanyaan ini akan penulis bahas dengan menelaah
kembali ayat Al-Qur’an yang menyangkut syariat untuk melakukan puasa.
Ayat Al-Qur’an yang memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan ibadah
puasa adalah surat Al-Baqarah ayat 183, yang berbunyi,”Hai orang-orang
yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa…”. Ayat tersebut turun
tanpa sebab-sebab tertentu, sebagaimana terjadi pada kebanyakan
ayat-ayat ahkâm –ayat yang berkenaan dengan hukum–, yang turun setelah
ada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi pada Nabi SAW atau para
sahabat.
Pada ayat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah [Madanî] ini
telah disebutkan sebuah informasi yang menyatakan “sebagaimana
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu”.
Ada dua [2] persoalan pokok pada ayat tersebut yang menjadi bahan
perbedaan pendapat di antara para ulama, khususnya para mufassir.
Perbedaan pertama menyangkut kalimat “sebagaimana diwajibkan”. Ini
menjadi persoalan karena munculnya pertanyaan; apakah kesamaan berpuasa
yang diwajibkan atas kaum “sebelum kamu” adalah puasa di bulan
Ramadlân, atau kesamaan itu hanya meliputi hal syariat berpuasa saja,
sedangkan waktunya berada di bulan lain [?].
Pada persoalan ini, perbedaan timbul di antara dua pendapat. Yang
pertama, dimotori Sa’îd bin Jabîr RA [w. 95 H.], yang cenderung
memaknai hukum tasybîh [penyerupaan atau penyamaan] itu hanya pada
kewajiban berpuasanya saja, dan tidak meliputi berapa lama dan pada
bulan apa berpuasa. Pendapat ini berdasar pada realitas sejarah dimana
masyarakat Jahiliyah masih mengenali syariat tersebut, walaupun telah
menjadi ‘sejarah’ serta tidak dilakukan di bulan Ramadlân yang sudah
dikenal. Bisa jadi pendapat ini menyandarkan kepada salah satu firman
Allah SWT tentang bermacam-macamnya syariat bagi masing-masing umat
manusia, “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu --maksudnya: umat Nabi
Muhammad SAW dan umat-umat yang sebelumnya--, Kami berikan aturan dan
jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu
terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat
kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” [QS.
5:48].
Pendapat kedua lebih terfokus pemahamannya kepada lama hari berpuasa
dan bulan diwajibkannya berpuasa. Lebih tepatnya, pendapat kedua ini
mengarahkan perhatiannya kepada ayat selanjutnya, pada ayat 184, yang
berbunyi, “[yaitu] dalam beberapa hari yang tertentu” [ayyâman
ma’dûdât]. Dengan demikian, secara global ulama kelompok ini
berpendapat bahwa puasa Ramadlan sebagaimana kaum muslimin lakukan
selama ini telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu.
Dasar pendapat ini tentu banyaknya riwayat yang menjelaskan tentang hal
itu. Antara lain sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullâh bin
‘Umar RA [w. 73 H.], sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsîr [701-774
H.] dalam tafsirnya, bahwa Nabi SAW bersabda “Puasa bulan Ramadlân
telah diwajibkan oleh Allah SWT atas umat sebelum kamu”.
Pada pendapat yang kedua ini masih terjadi ikhtilâf [perbedaan], apakah
selama “beberapa hari yang tertentu” [ayyâman ma’dûdât] berpuasa
--yang diwajibkan pada kaum dahulu itu-- adalah berupa sebulan penuh
dalam Ramadlân atau bulan-bulan lainnya [?].
Ada dua [2] pendapat, pertama menyatakan bahwa puasa yang disyariatkan
pada umat terdahulu adalah berupa puasa selama tiga [3] hari pada
setiap bulan. Abdullâh bin ‘Abbâs RA [w. 69 H.] mengatakan, ”Syariat
sebelumnya adalah puasa tiga hari setiap bulan, lalu syariat ini
di-nasakh dengan syariat yang baru, melalui surat Al-Baqarah ayat 185”
[Tafsîr Zâd-l-Mashîr]. Pendapat kedua mengklaim bahwa “hari-hari
tertentu” yang dimaksud adalah bulan Ramadlân itu sendiri. Jadi, pada
bulan Ramadlân jugalah umat-umat dahulu diwajibkan berpuasa.
Al-Suday menyatakan bahwa orang-orang Nasrani sebenarnya telah memiliki
syariat puasa di bulan Ramadlân. Tetapi, karena mereka merasakan
berat, mereka kemudian merubahnya dengan berpuasa di waktu antara musim
dingin dan musim panas, serta menambah beberapa hari. Beberapa hari
tambahan itu dengan perincian masing-masing sepuluh hari sebelum dan
sesudah bulan yang disepakati ulama mereka. Sehingga, mereka berpuasa
selama lima puluh hari. Ibnu Jarîr [224-310 H.] secara lebih berani
meyakini seyakin-yakinnya adanya syariat puasa di bulan Ramadlan bagi
Nasrani [Tafsîr al-Thabarî]. Sedangkan agamawan Yahudi, yang juga
memiliki syariat puasa di bulan Ramadlân, menggantinya dengan puasa
sehari dalam setahun. Hal itu, dalam informasi yang dimiliki
Syihâbuddîn Al-Âlûsî [w. 1270 H.], penulis Tafsîr Rûh-l-Ma’ânî,
merupakan klaim mereka bahwa hari itu adalah hari tenggelamnya Fir’aun
dan tentaranya di laut Merah.
Perbedaan kedua –dalam menelaah ayat syariat puasa itu– adalah tentang
siapa yang dimaksud dengan “orang-orang sebelum kamu”. Pendapat pertama
mengatakan yang dimaksud adalah ”orang-orang ahlul kitâb”, yaitu
mereka-mereka yang masih berpegang kepada kitab agama-agama sebelum
Islam [Yahudi dan Nasrani]. Pendapat kedua menyebutkan kaum Nasrani-lah
yang dimaksud ayat itu. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan
bahwa ayat itu memaksudkan seluruh umat-umat manusia sebelum umat
Muhammad SAW.
Dalam kitab Perjanjian, salah satunya di Ezra 8:21, memang
diinformasikan secara indikatif adanya syariat-syariat puasa dalam
Kristen, tetapi tidak secara terperinci disebutkan apa yang dimaksud
dengan puasa, selama berapa lama dan diwajibkan pada bulan apa.
“Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa
supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon
kepada-Nya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala
harta benda kami”. Penulis belum menemukan keterangan-keterangan lain
di kitab Perjanjian yang menerangkan lebih jauh tentang puasa tersebut.
Dalam konteks sejarah yang lain, syariat puasa nampaknya benar-benar
menjadi syariat setiap umat. Sayyidah ‘Aisyah RA menceritakan –seperti
yang diriwayatkan oleh Hisyâm bin ‘Urwah—bahwa orang-orang Quraisy
biasa menjalankan puasa di bulan ‘Âsyûrâ, walaupun sehari saja. Namun
sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, puasa dilaksanakan pada bulan
Ramadlân. Puasa di bulan ‘Âsyûrâ masih disyariatkan tetapi berada dalam
status sunnah.
Masih ada riwayat lain yang menerangkan tentang syariat puasa pada umat
dahulu. Al-Dlahâk, dalam riwayat Ibnu Abî Hâtim, mengatakan bahwa
puasa pertama kali disyariatkan di zaman Nabi Nuh AS, dan masih tetap
berlangsung hingga zaman nabi Muhammad SAW. Syihâbuddîn Al-Âlûsî [w.
1270 H.], penulis Tafsîr Rûh-l-Ma’ânî, dengan berdasar hadits Nabi SAW
yang diriwayatkan oleh Abdullâh bin ‘Umar itu, lebih percaya bahwa puasa
Ramadlân disyariatkan sejak Nabi Adam AS. Al-Zamakhsarî [467-538 H.]
melalui telaahnya atas asal usul bulan Ramadlân juga menegaskan bahwa
puasa adalah amal ibadah yang sudah lama [‘Ibâdah Qadîmah ].
Dengan melihat hadits yang diriwayatkan Abdullâh bin ‘Umar dan beberapa
riwayat lain serta melihat proses turunnya syariat yang tanpa diawali
sebab-sebab tertentu serta beberapa hal lain –yang semuanya telah
penulis singgung di atas, nampak jelas bahwa “puasa pada bulan Ramadlân”
telah disyariatkan kembali kepada manusia –tidak hanya kepada umat
Muhammad SAW– setelah sebelumnya dibelokkan oleh umat-umat terdahulu.
Ini lebih bisa diterima karena kemunculan Nabi Muhammad SAW adalah
meluruskan dan memperkuat kembali syariat-syariat dari Tuhan yang
–sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur’an– telah di-tahrif atau
diselewengkan oleh umat-umat terdahulu. Nah, pelurusan dan penguatan
syariat pada era Islam ini melahirkan dugaan dari para sarjana Barat,
bahwa syariat agama Islam tidaklah murni melainkan mengadopsi dari
agama-agama sebelumnya.
Mengenai kata Ramadlân, sebagaimana tersurat dalam hadits Nabi SAW di
atas –riwayat Abdullâh bin ‘Umar RA– dan juga surat Al-Baqarah ayat
185, penulis merasa istilah itu mengikuti budaya Arab yang sudah
mengenal tradisi ber-Ramadlân. Yang penulis maksudkan adalah, ketika
Al-Qur’an atau Nabi SAW menyebut kata Ramadlân, masyarakat sudah tidak
asing lagi dengan istilah ini. Bahkan dalam konteks struktur bahasa
Arab, kata ini sudah menjadi Ism ghoiri munsharif. Artinya, makna dan
maksud kata itu sudah cukup terkenal dan tidak perlu lagi mengikuti
kaidah-kaidah gramatikal bahasa Arab.
Dengan demikian, kita bisa memastikan pula bahwa bulan Ramadlân itu
ada, setidaknya, sejak syariat puasa diturunkan kepada umat manusia.
Karena, makna Ramadlân itu sendiri adalah waktu atau keadaan atau hal
dimana seseorang merasakan panas, mulut terasa kering dan tenggorokan
terasa haus, yang dikarenakan sedang berpuasa. Sehingga, dengan
sendirinya dan secara otomatis, bulan atau waktu dimana orang melakukan
puasa disebut bulan atau waktu Ramadlân, yaitu saat yang panas, kering
dan haus.
Telah kita ketahui bahwa syariat puasa memang sudah menjadi syariat
bagi setiap umat manusia. Dan di antara sekian macam syariat, hanya
ibadah puasa merupakan ibadah kontemplatif. Hal ini bisa dibenarkan,
karena dalam sebuah hadits Qudsy, Allah SWT telah berfirman, “Seluruh
amal ibadah anak-anak keturunan Adam diperuntukkan kepada pelakunya,
kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku, dan Aku
mengganjar karenanya”. Sehingga, dengan pernyataan Allah SWT itu, Imâm
al-Qurthubî [627-671 H.] dalam tafsirnya mengatakan bahwa ‘puasa
merupakan [komunikasi] rahasia antara hamba dengan Tuhannya’. Itulah,
dan sudah selayaknya sangat bisa diterima jika Shuhuf-nya Ibrahim AS,
Taurat untuk Musa AS, Injîl untuk Isa AS serta Al-Qur’an pun turun
pertama kali pada bulan Ramadlân, bulan saat para pembebas sedang
berkontemplasi.